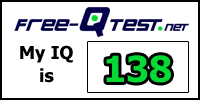Pemikiran filsafat klasik merupakan salah satu kekayaan kebudayaan Cina kuno yang paling bisa dibanggakan. Biasanya orang selalu merujuknya pada Konfusianisme, yang sebenarnya hanya merupakan salah satu dari banyak aliran yang muncul di Cina kuno. Sebenarnya seperti apakah awal dari kemunculan banyak aliran tersebut?
Pemikiran Cina kuno mulai berkembang sejak masa dinasti Zhou Timur (770 – 256 SM), tepatnya pada masa Musim Semi dan Musim Gugur (nama yang diambil dari Spring and Autumn Annals). Pada masa ini, pemikiran dan berbagai negara bermunculan (semi) dan hancur (gugur) dengan banyaknya, hingga muncul perkataan “seratus bunga bermekaran seratus pemikiran bermunculan”. Pada masa ini juga muncul nama-nama besar seperti Kong Zi (Konfusianisme), Lao Zi (Dao), Mo Zi (Mohisme), Han Feizi (Legalisme) hingga jenderal besar seperti Sun Zi.
Perlu diingat bahwa bangsa Cina adalah bangsa yang menerapkan pemikiran yang inward looking sehingga dalam menghadapi masalah mereka selalu melihat pemecahannya dari dalam diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku juga pada masa itu. Peperangan yang terus berlangsung (hingga akhirnya kekuasaan mengerucut hingga 7 negara pada Warring States / Zhan Guo, yang akan dibahas pada posting lain) dicari akar permasalahannya dan pemecahannya dari dalam diri mereka sendiri.
Kesimpulan yang ditarik oleh sebagian besar dari pemikir-pemikir klasik itu adalah rusak dan korupnya masyarakat, yang menyebabkan runtuhnya kekuatan Cina sebagai pusat dunia (Zhongguo). Pemecahan masalah tersebut ada pada perbaikan yang dilakukan oleh diri sendiri, dengan cara yang berbeda pada masing-masing aliran. Pada akhirnya aliran-aliran ini sendiri berebut pengaruh dan dipedomani oleh masing-masing negara.
Pemikiran-pemikiran ini terus berkembang dengan coraknya masing-masing, dan pada akhirnya, aliran yang berkembang pesat dan bertahan bahkan hingga kini adalah Konfusianisme (yang telah diperbarui pada zaman Tang), Daoisme (yang kini banyak berkembang, bahkan menjadi agama sendiri) dan Buddhisme (yang telah mengalami sinifikasi dan berbeda dengan corak agam Buddha India). Dari semua aliran ini, yang bukan berasal dari Cina dan muncul pada masa yang berbeda (Buddhisme datang pada masa dinasti Han Barat pada abad ke-1) hanyalah Buddhisme dan itupun telah mengalami sinifikasi sehingga sangat kental dengan warna “Cina” di dalamya.
Pola-pola pemikiran inilah yang kemudian menjadi dasar dari segala perbuatan orang Cina. Satu hal yang menjadi persamaan dari aliran-aliran ini adalah penekanannya pada hal moralitas. Ini berbeda dengan corak filsafat Barat yang menekankan pada kontemplasi dan pencarian kebenaran. Pola filsafat Cina muncul untuk menjawab pertanyaan mengenai kenegaraan dan bagaimana “mengatur” manusia (sistem kontrol sosial masyarakat), coba bandingkan dengan pola Socrates, Plato dan Aristoteles yang pada awalannya lebih bersifat metafisis.
Perlu diingat bahwa filsafat ini muncul untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengatur manusia dan menciptakan negara yang kuat (dipercaya bahwa sejak dulu tujuan dari para intelektual adalah membuat negara kaya dan kuat / fu qiang). Oleh karena itu, tidak heran bahwa filsafat yang muncul juga membawa corak yang sama. Misalnya saja, Konfusianisme yang menekankan pada pendidikan moral untuk menciptakan masyarakat sejahtera, atau oposannya, legalisme, yang menekankan pada penerapan hukum untuk mengatur masyarakat dan manusia yang “jahat”.
Bahasan mengenai kebudayaan dan pemikiran Cina akan sangat sulit dan panjang untuk dijelaskan. Untuk selanjutnya saya mengharapkan komentar dan pertanyaan serta tanggapan dari pembaca mengenai kebudayaan Cina. Saya akan coba menanggapi dengan penjelasan yang lebih rinci lagi.
Minggu, 20 April 2008
Koordinasi dan Komunikasi Massa pada Masa Mao Zedong
Bagaimanakah komunikasi dan koordinasi massa pada masa China-Mao Zedong? Benarkah sebagai sebuah Negara sosialis mereka menggunakan tangan besi dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat untuk melakuakn sesuai dengan keinginan penguasa? Ataukah ada cara lain yang dilakukan oleh rezim pemerintah China-Mao untuk mengarahkan keinginan masyarakat?
Pertanyaan itu bisa dijawab dengan memperhatikan tulisan dari Charles Lindblom mengenai koordinasi massa pada Politics and Market. Dalam buku ini, beliau menjelaskan tentang cara koordinasi massa yang lazim digunakan pada dunia massa Perang Dingin.
Dalam bukunya, Lindblom menyatakan bahwa koordinasi massa dilakukan dengan 3 macam mekanisme: Pasar, kekuasaan dan perseptoral. Pada mekanisme pasar, Negara lepas tangan terhadap kegiatan masyarakat dan politik. Ini berbeda 180º dengan system authority yang mengandalkan pada kuasa Negara untuk mengatur masyarakatnya. Sementara itu, beliau menulis bahwa ada satu lagi cara komando masyarakat yaitu dengan perseptoral (persuasi).
Sistem ini digunakan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Mulai dari propaganda melalui surat kabar (yang mana pada waktu itu semua dikendalikan di bawah pemerintah dengan “rajanya” Renmin Ribao) hingga pembentukan kelompok diskusi dengan “konsul2” yang ditunuk dan dibiayai pemerintah pada apa yang disebut sebagai “ritual Maois”.
Segala macam kegiatan ini dilakukan untuk mendoktrin masyarakat China dengan sosialisme dan sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran Mao Zedong. Di sini, propaganda dilakukan dengan diperkuat oleh system authority yang sangat kuat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan itu (biasanya setelah bertani).
Setelah sosialisme berhasil ditanamkan dengan cukup kuat, baru dilakukan penerapan system perseptoral pada masyarakat Cina. Kader militant yang diperlukan untuk memberikan “persuasi” dan propaganda telah tersedia dengan baik dan siap untuk digunakan oleh partai. Mulai saat inilah dilakukan penerapan perseptoral. Kelompok-kelompok diskusi yang tadinya digunakan untuk memberikan doktrinasi kini digeser fungsinya menjadi lembaga mobilisasi massa dengan cara memberikan insentif material (sebelum komune) dan insentif moral.
System ini juga yang membuat system komune berhasil diterapkan dengan mulus. Bermula dari penerapan komune di daerah Hsing-yang yang cukup berhasil. Keberhasilan komune percontohan ini dipublikasikan besar-besaran dan dipuji secara berlebihan oleh Mao Zedong. Pada akhirnya, dengan propaganda dan publikasi positif seperti itu, rakyat daerah lain berlomba-lomba meminta daerahnya dijadikan komune, dan PKC berhasil membuat komune di seluruh Cina menjadi kenyataan.
Pertanyaan itu bisa dijawab dengan memperhatikan tulisan dari Charles Lindblom mengenai koordinasi massa pada Politics and Market. Dalam buku ini, beliau menjelaskan tentang cara koordinasi massa yang lazim digunakan pada dunia massa Perang Dingin.
Dalam bukunya, Lindblom menyatakan bahwa koordinasi massa dilakukan dengan 3 macam mekanisme: Pasar, kekuasaan dan perseptoral. Pada mekanisme pasar, Negara lepas tangan terhadap kegiatan masyarakat dan politik. Ini berbeda 180º dengan system authority yang mengandalkan pada kuasa Negara untuk mengatur masyarakatnya. Sementara itu, beliau menulis bahwa ada satu lagi cara komando masyarakat yaitu dengan perseptoral (persuasi).
Sistem ini digunakan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Mulai dari propaganda melalui surat kabar (yang mana pada waktu itu semua dikendalikan di bawah pemerintah dengan “rajanya” Renmin Ribao) hingga pembentukan kelompok diskusi dengan “konsul2” yang ditunuk dan dibiayai pemerintah pada apa yang disebut sebagai “ritual Maois”.
Segala macam kegiatan ini dilakukan untuk mendoktrin masyarakat China dengan sosialisme dan sikap-sikap yang sesuai dengan ajaran Mao Zedong. Di sini, propaganda dilakukan dengan diperkuat oleh system authority yang sangat kuat dan memaksa masyarakat untuk mengikuti segala kegiatan itu (biasanya setelah bertani).
Setelah sosialisme berhasil ditanamkan dengan cukup kuat, baru dilakukan penerapan system perseptoral pada masyarakat Cina. Kader militant yang diperlukan untuk memberikan “persuasi” dan propaganda telah tersedia dengan baik dan siap untuk digunakan oleh partai. Mulai saat inilah dilakukan penerapan perseptoral. Kelompok-kelompok diskusi yang tadinya digunakan untuk memberikan doktrinasi kini digeser fungsinya menjadi lembaga mobilisasi massa dengan cara memberikan insentif material (sebelum komune) dan insentif moral.
System ini juga yang membuat system komune berhasil diterapkan dengan mulus. Bermula dari penerapan komune di daerah Hsing-yang yang cukup berhasil. Keberhasilan komune percontohan ini dipublikasikan besar-besaran dan dipuji secara berlebihan oleh Mao Zedong. Pada akhirnya, dengan propaganda dan publikasi positif seperti itu, rakyat daerah lain berlomba-lomba meminta daerahnya dijadikan komune, dan PKC berhasil membuat komune di seluruh Cina menjadi kenyataan.
China-Tibet: Budaya vs Modernisasi
Persoalan China – Tibet yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini memang sudah sangat panjang. Siapa yang menyangka bahwa akar permasalahan dari berbagai keributan yang muncul menjelang Olimpiade Beijing ini ternyata adalah sebuah gerakan kaum komunis China yang dilakukan pada tahun 1950? Kenyataan inilah yang akan coba dibahas pada tulisan kali ini.
Pada saat perang pembebasan China pada 1949, salah satu janji yang diberikan oleh pihak PKC adalah persamaan hak dari setiap orang, yang diwujudkan dalam penghapusan kelas masyarakat. Secara praktis, ini berarti merombak susunan social masyarakat lama yang bertumpu pada penguasa tuan tanah sebagai “raja kecil” pada daerah yang dimilikinya. Dalam hal ini, mereka berlaku sebagai kaum kapitalis (karena mereka satu-satunya yang memiliki kapital, tanah) dan para petani penggarap dan penyewa adalah kaum buruh (yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis).
Secara praktis, janji ini dipraktekkan dalam sebuah gerakan yang dinamakan land reform. Gerakan ini, di samping perang pembebasan dan pengusiran Jepang dari tanah China, menjadi legitimasi valid dari kekuasaan PKC di tanah China. Berkat tiga hal itulah kekuasaan PKC di tanah RRC diakui oleh rakyat banyak. Gerakan ini kemudian dilakukan ke seluruh penjuru China, dan pada aneksasi (baca: pembebasan) Tibet pada 1950, gerakan ini juga dilakukan.
Pada awal masuknya tangan-tangan PKC ke tanah Tibet, Dalai Lama sebagai Lama yang tertinggi mengakui kekuasaan PKC atas tanah PKC. Sayangnya, ketika gerakan ini direalisasikan, ternyata mengalami resistensi dari kaum aristokrat. Kaum aristokrat ini adalah kaum bangsawan yang menguasai penguasaan tanh dan berbagai harta kekayaan lain (sistem sosial masyarakat Tibet adalah penguasaan kekayaan dan kapital ekonomi pada golongan Lama/petinggi agama dan aristokrat/bangsawan yang hanya berjumlah 3% – 5% dari seluruh jumlah penduduk Tibet pada masa itu).
Yang menjadi masalah, sebagaimanahalnya berbagai kebudayaan di mana agama memegang peran sebagai penyambung kepercayaan rakyat, apalagi ditambah penokohan kharismatik pada diri Dalai Lama, rakyat mengakui dan menjalani kehidupan dengan senang hati. Kelihatannya, terlepas dari berbagai perubahan dan modernisasi yang dilakukan China, masyarakat Tibet masih tetap berpegang pada kepercayaan pada Dalai Lama dan masih berpegang pada kebudayaan lama yang religius.
Pada masa awal land reform inilah susunan masyarakat Tibet mengalami fase perombakan sosial besar-besaran. Dengan mengumandangkan semangat revolusi dengan cara kekerasan ala Marx, pelaksanaan land reform dilakukan dengan cara-cara yang brutal, yang ditujukan kepada kaum aristokrat dan kaum Lama yang selama ini menjadi pihak yang hidup sejahtera.
Pelaksanaan land reform yang dilakukan dengan cara kekerasan inilah yang menimbulkan resistensi besar dari rakyat Tibet. Berdasarkan film semi-dokumenter “Kundun”, pelaksanaan gerakan dilakukan dengan cara pembunuhan dan tentu saja ini berlawanan dengan sikap hidup mereka selama ini yang berdasarkan pada sikap anti kekerasan. Jelas saja, tindakan-tindakan tentara pembebasan (PLA) mendapat perlawanan dari rakyat.
Dari paparan di atas, bisa dilihat bahwa permasalahan China-Tibet adalah permasalahan yang berdasar dari permasalahan budaya yang berlawanan. Budaya Marxisme-Komunisme mendasarkan revolusi yang harus dilakukan dengan kekerasan, sementara budaya Tibet mendasarkan diri pada sikap anti kekerasan yang sangat kental, sesuai dengan citra Dalai Lama yang dikabarkan merupakan titisan dari Buddha kasih sayang (walaupun Buddha Lamaisme cukup berbeda dengan ajaran Buddha pada umumnya, misalnya saja makan daging atau perlakuan terhadap orang yang meninggal).
Permasalahan ini sangat terlihat dalam pelaksanaan land reform tersebut. Militer China (PLA) melakukan berbagai kekerasan, sementara pihak sipil Tibet melakukan tindakan tidak melawan. Tentu saja kondisi yang berbeda belum tentu akan ditemukan pada masa ini, apalagi bila melihat dari kenyataan di lapangan bahwa belum tentu yang melakukan tindakan anarki di Tibet (pada masa kini) adalah tentara Tibet, tapi merupakan propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh sipil untuk mendiskreditkan China.
Misalnya saja, dari toko yang dirusak. Kenyataannya, kebanyakan toko yang dirusak adalah toko milik orang Han (suku mayoritas di China), dan bukan milik suku minoritas Tibet. Berbagai foto yang muncul ke luar juga adalah foto rekayasa atau foto palsu yang bukan dari kejadian yang sebenarnya. Wartawan, yang katanya dihalang-halangi untuk masuk ke Tibet, juga ternyata tidak mengalami halangan berarti (kesaksian seorang wartawan senior Kompas). Jadi apa benar bahwa militer China melakukan tindakan represif dan anarkis di Tibet?
Sebaliknya, banyak juga kejadian “anti-China” yang muncul akhir-akhir ini ternyata hanyalah akal-akalan. Misalnya saja kejadian “rebutan” obor Olimpiade yang terjadi baru-baru ini. Banyak yang mengatakan bahwa orang yang “merebut” ternyata juga adalah orang yang ikut terlibat dalam demo pro-China. Ini mungkin dilakukan untuk memobilisasi rakyat dan meningkatkan rasa nasiolnalisme penduduk China.
Apapun, yang menjadi masalah adalah nasib Tibet sendiri. Pertarungan budaya vs modernisme yang diusung masing-masing pihak pada akhirnya akan kembali ke rakyat Tibet sendiri. Yang manakah yang akan menjadi masa depan Tibet? Bersama China dan menjadi besar, atau merdeka dan menjadi penentu nasibnya sendiri.
Pada saat perang pembebasan China pada 1949, salah satu janji yang diberikan oleh pihak PKC adalah persamaan hak dari setiap orang, yang diwujudkan dalam penghapusan kelas masyarakat. Secara praktis, ini berarti merombak susunan social masyarakat lama yang bertumpu pada penguasa tuan tanah sebagai “raja kecil” pada daerah yang dimilikinya. Dalam hal ini, mereka berlaku sebagai kaum kapitalis (karena mereka satu-satunya yang memiliki kapital, tanah) dan para petani penggarap dan penyewa adalah kaum buruh (yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis).
Secara praktis, janji ini dipraktekkan dalam sebuah gerakan yang dinamakan land reform. Gerakan ini, di samping perang pembebasan dan pengusiran Jepang dari tanah China, menjadi legitimasi valid dari kekuasaan PKC di tanah China. Berkat tiga hal itulah kekuasaan PKC di tanah RRC diakui oleh rakyat banyak. Gerakan ini kemudian dilakukan ke seluruh penjuru China, dan pada aneksasi (baca: pembebasan) Tibet pada 1950, gerakan ini juga dilakukan.
Pada awal masuknya tangan-tangan PKC ke tanah Tibet, Dalai Lama sebagai Lama yang tertinggi mengakui kekuasaan PKC atas tanah PKC. Sayangnya, ketika gerakan ini direalisasikan, ternyata mengalami resistensi dari kaum aristokrat. Kaum aristokrat ini adalah kaum bangsawan yang menguasai penguasaan tanh dan berbagai harta kekayaan lain (sistem sosial masyarakat Tibet adalah penguasaan kekayaan dan kapital ekonomi pada golongan Lama/petinggi agama dan aristokrat/bangsawan yang hanya berjumlah 3% – 5% dari seluruh jumlah penduduk Tibet pada masa itu).
Yang menjadi masalah, sebagaimanahalnya berbagai kebudayaan di mana agama memegang peran sebagai penyambung kepercayaan rakyat, apalagi ditambah penokohan kharismatik pada diri Dalai Lama, rakyat mengakui dan menjalani kehidupan dengan senang hati. Kelihatannya, terlepas dari berbagai perubahan dan modernisasi yang dilakukan China, masyarakat Tibet masih tetap berpegang pada kepercayaan pada Dalai Lama dan masih berpegang pada kebudayaan lama yang religius.
Pada masa awal land reform inilah susunan masyarakat Tibet mengalami fase perombakan sosial besar-besaran. Dengan mengumandangkan semangat revolusi dengan cara kekerasan ala Marx, pelaksanaan land reform dilakukan dengan cara-cara yang brutal, yang ditujukan kepada kaum aristokrat dan kaum Lama yang selama ini menjadi pihak yang hidup sejahtera.
Pelaksanaan land reform yang dilakukan dengan cara kekerasan inilah yang menimbulkan resistensi besar dari rakyat Tibet. Berdasarkan film semi-dokumenter “Kundun”, pelaksanaan gerakan dilakukan dengan cara pembunuhan dan tentu saja ini berlawanan dengan sikap hidup mereka selama ini yang berdasarkan pada sikap anti kekerasan. Jelas saja, tindakan-tindakan tentara pembebasan (PLA) mendapat perlawanan dari rakyat.
Dari paparan di atas, bisa dilihat bahwa permasalahan China-Tibet adalah permasalahan yang berdasar dari permasalahan budaya yang berlawanan. Budaya Marxisme-Komunisme mendasarkan revolusi yang harus dilakukan dengan kekerasan, sementara budaya Tibet mendasarkan diri pada sikap anti kekerasan yang sangat kental, sesuai dengan citra Dalai Lama yang dikabarkan merupakan titisan dari Buddha kasih sayang (walaupun Buddha Lamaisme cukup berbeda dengan ajaran Buddha pada umumnya, misalnya saja makan daging atau perlakuan terhadap orang yang meninggal).
Permasalahan ini sangat terlihat dalam pelaksanaan land reform tersebut. Militer China (PLA) melakukan berbagai kekerasan, sementara pihak sipil Tibet melakukan tindakan tidak melawan. Tentu saja kondisi yang berbeda belum tentu akan ditemukan pada masa ini, apalagi bila melihat dari kenyataan di lapangan bahwa belum tentu yang melakukan tindakan anarki di Tibet (pada masa kini) adalah tentara Tibet, tapi merupakan propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh sipil untuk mendiskreditkan China.
Misalnya saja, dari toko yang dirusak. Kenyataannya, kebanyakan toko yang dirusak adalah toko milik orang Han (suku mayoritas di China), dan bukan milik suku minoritas Tibet. Berbagai foto yang muncul ke luar juga adalah foto rekayasa atau foto palsu yang bukan dari kejadian yang sebenarnya. Wartawan, yang katanya dihalang-halangi untuk masuk ke Tibet, juga ternyata tidak mengalami halangan berarti (kesaksian seorang wartawan senior Kompas). Jadi apa benar bahwa militer China melakukan tindakan represif dan anarkis di Tibet?
Sebaliknya, banyak juga kejadian “anti-China” yang muncul akhir-akhir ini ternyata hanyalah akal-akalan. Misalnya saja kejadian “rebutan” obor Olimpiade yang terjadi baru-baru ini. Banyak yang mengatakan bahwa orang yang “merebut” ternyata juga adalah orang yang ikut terlibat dalam demo pro-China. Ini mungkin dilakukan untuk memobilisasi rakyat dan meningkatkan rasa nasiolnalisme penduduk China.
Apapun, yang menjadi masalah adalah nasib Tibet sendiri. Pertarungan budaya vs modernisme yang diusung masing-masing pihak pada akhirnya akan kembali ke rakyat Tibet sendiri. Yang manakah yang akan menjadi masa depan Tibet? Bersama China dan menjadi besar, atau merdeka dan menjadi penentu nasibnya sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)