Persoalan China – Tibet yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini memang sudah sangat panjang. Siapa yang menyangka bahwa akar permasalahan dari berbagai keributan yang muncul menjelang Olimpiade Beijing ini ternyata adalah sebuah gerakan kaum komunis China yang dilakukan pada tahun 1950? Kenyataan inilah yang akan coba dibahas pada tulisan kali ini.
Pada saat perang pembebasan China pada 1949, salah satu janji yang diberikan oleh pihak PKC adalah persamaan hak dari setiap orang, yang diwujudkan dalam penghapusan kelas masyarakat. Secara praktis, ini berarti merombak susunan social masyarakat lama yang bertumpu pada penguasa tuan tanah sebagai “raja kecil” pada daerah yang dimilikinya. Dalam hal ini, mereka berlaku sebagai kaum kapitalis (karena mereka satu-satunya yang memiliki kapital, tanah) dan para petani penggarap dan penyewa adalah kaum buruh (yang diperas tenaganya oleh kaum kapitalis).
Secara praktis, janji ini dipraktekkan dalam sebuah gerakan yang dinamakan land reform. Gerakan ini, di samping perang pembebasan dan pengusiran Jepang dari tanah China, menjadi legitimasi valid dari kekuasaan PKC di tanah China. Berkat tiga hal itulah kekuasaan PKC di tanah RRC diakui oleh rakyat banyak. Gerakan ini kemudian dilakukan ke seluruh penjuru China, dan pada aneksasi (baca: pembebasan) Tibet pada 1950, gerakan ini juga dilakukan.
Pada awal masuknya tangan-tangan PKC ke tanah Tibet, Dalai Lama sebagai Lama yang tertinggi mengakui kekuasaan PKC atas tanah PKC. Sayangnya, ketika gerakan ini direalisasikan, ternyata mengalami resistensi dari kaum aristokrat. Kaum aristokrat ini adalah kaum bangsawan yang menguasai penguasaan tanh dan berbagai harta kekayaan lain (sistem sosial masyarakat Tibet adalah penguasaan kekayaan dan kapital ekonomi pada golongan Lama/petinggi agama dan aristokrat/bangsawan yang hanya berjumlah 3% – 5% dari seluruh jumlah penduduk Tibet pada masa itu).
Yang menjadi masalah, sebagaimanahalnya berbagai kebudayaan di mana agama memegang peran sebagai penyambung kepercayaan rakyat, apalagi ditambah penokohan kharismatik pada diri Dalai Lama, rakyat mengakui dan menjalani kehidupan dengan senang hati. Kelihatannya, terlepas dari berbagai perubahan dan modernisasi yang dilakukan China, masyarakat Tibet masih tetap berpegang pada kepercayaan pada Dalai Lama dan masih berpegang pada kebudayaan lama yang religius.
Pada masa awal land reform inilah susunan masyarakat Tibet mengalami fase perombakan sosial besar-besaran. Dengan mengumandangkan semangat revolusi dengan cara kekerasan ala Marx, pelaksanaan land reform dilakukan dengan cara-cara yang brutal, yang ditujukan kepada kaum aristokrat dan kaum Lama yang selama ini menjadi pihak yang hidup sejahtera.
Pelaksanaan land reform yang dilakukan dengan cara kekerasan inilah yang menimbulkan resistensi besar dari rakyat Tibet. Berdasarkan film semi-dokumenter “Kundun”, pelaksanaan gerakan dilakukan dengan cara pembunuhan dan tentu saja ini berlawanan dengan sikap hidup mereka selama ini yang berdasarkan pada sikap anti kekerasan. Jelas saja, tindakan-tindakan tentara pembebasan (PLA) mendapat perlawanan dari rakyat.
Dari paparan di atas, bisa dilihat bahwa permasalahan China-Tibet adalah permasalahan yang berdasar dari permasalahan budaya yang berlawanan. Budaya Marxisme-Komunisme mendasarkan revolusi yang harus dilakukan dengan kekerasan, sementara budaya Tibet mendasarkan diri pada sikap anti kekerasan yang sangat kental, sesuai dengan citra Dalai Lama yang dikabarkan merupakan titisan dari Buddha kasih sayang (walaupun Buddha Lamaisme cukup berbeda dengan ajaran Buddha pada umumnya, misalnya saja makan daging atau perlakuan terhadap orang yang meninggal).
Permasalahan ini sangat terlihat dalam pelaksanaan land reform tersebut. Militer China (PLA) melakukan berbagai kekerasan, sementara pihak sipil Tibet melakukan tindakan tidak melawan. Tentu saja kondisi yang berbeda belum tentu akan ditemukan pada masa ini, apalagi bila melihat dari kenyataan di lapangan bahwa belum tentu yang melakukan tindakan anarki di Tibet (pada masa kini) adalah tentara Tibet, tapi merupakan propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh sipil untuk mendiskreditkan China.
Misalnya saja, dari toko yang dirusak. Kenyataannya, kebanyakan toko yang dirusak adalah toko milik orang Han (suku mayoritas di China), dan bukan milik suku minoritas Tibet. Berbagai foto yang muncul ke luar juga adalah foto rekayasa atau foto palsu yang bukan dari kejadian yang sebenarnya. Wartawan, yang katanya dihalang-halangi untuk masuk ke Tibet, juga ternyata tidak mengalami halangan berarti (kesaksian seorang wartawan senior Kompas). Jadi apa benar bahwa militer China melakukan tindakan represif dan anarkis di Tibet?
Sebaliknya, banyak juga kejadian “anti-China” yang muncul akhir-akhir ini ternyata hanyalah akal-akalan. Misalnya saja kejadian “rebutan” obor Olimpiade yang terjadi baru-baru ini. Banyak yang mengatakan bahwa orang yang “merebut” ternyata juga adalah orang yang ikut terlibat dalam demo pro-China. Ini mungkin dilakukan untuk memobilisasi rakyat dan meningkatkan rasa nasiolnalisme penduduk China.
Apapun, yang menjadi masalah adalah nasib Tibet sendiri. Pertarungan budaya vs modernisme yang diusung masing-masing pihak pada akhirnya akan kembali ke rakyat Tibet sendiri. Yang manakah yang akan menjadi masa depan Tibet? Bersama China dan menjadi besar, atau merdeka dan menjadi penentu nasibnya sendiri.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
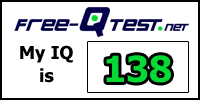
Tidak ada komentar:
Posting Komentar